PAKAR hukum tata negara Mohammad Mahfud Mahmodin atau Mahfud MD menyebutkan jadwal keserentakan pemilu seharusnya open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang alih-alih Mahkamah Konstitusi (MK).
“MK itu tidak punya wewenang. Karena apa? Itu open legal policy. Urusan jadwal pemilu itu kan urusan eksekutif, urusan pembentuk undang-undang,” kata Mahfud dalam diskusi publik di Jakarta pada Kamis, 24 Juli 2025, seperti dikutip dari Antara.
Menurut Mahfud, MK tidak boleh membatalkan suatu norma undang-undang yang dianggap tidak baik. Dia menuturkan Mahkamah hanya berwenang membatalkan norma undang-undang yang terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. “Yang jelas-jelas melanggar konstitusi, boleh oleh MK itu dibatalkan,” ucap ketua MK periode 2008-2013 itu.
Sebelumnya, MK memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional harus dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota (pemilu lokal). Mahkamah memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional.
Hal itu merupakan bagian dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis, 26 Juni 2025. Mahkamah mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Perihal jadwal pemilu, Mahfud menyinggung putusan MK sebelumnya yang berbeda dengan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam pertimbangan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah memberikan enam pilihan model keserentakan pemilu.
“Katanya tadi konstitusional semua, lalu dipilih satu, lalu ditentukan jadwalnya, itu sebenarnya tidak boleh, (MK) tidak punya wewenang,” kata Mahfud.
Meski demikian, Mahfud menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga harus dijalankan dengan melakukan rekayasa konstitusional, sebagaimana yang diamanatkan pula oleh MK dalam Putusan Nomor 135 itu.
Lima Alternatif untuk Rekayasa Konstitusional
Mengenai rekayasa konstitusional, Mahfud mengemukakan lima alternatif, yakni memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah dengan undang-undang; kepala daerah diganti penjabat, DPRD dipilih melalui pemilu sela; kepala daerah diperpanjang dengan penjabat, DPRD diperpanjang dengan undang-undang tanpa pemilu sela; pemilu sela untuk DPRD dan kepala daerah periode peralihan; serta pilkada oleh DPRD.
Namun Mahfud tidak merekomendasikan pembentuk undang-undang memilih opsi terakhir, yakni pilkada oleh DPRD karena terlalu ekstrem. “Itu akan mundur. Saya tidak merekomendasikan, cuma itu bisa menjadi alternatif yang boleh. Saya lebih suka pemilu seperti sekarang, sama-sama langsung, tetapi jadwalnya menjadi problem,” ujarnya.
Pemilu nasional adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta presiden dan wakil presiden. Sedangkan pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.
Putusan Pemisahan Pemilu Inkonstitusional
Meski demikian, Mahfud menilai putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah berpotensi inkonstitusional. Alasannya, pemisahan pemilu dapat berakibat pada perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, dari lima tahun menjadi tahun.
“Memang terasa putusan MK ini dituding inkonstitusional. (Tudingan) itu rasanya memang ada alasannya,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, putusan MK tersebut dapat dinilai inkonstitusional karena berimplikasi terhadap perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Sehingga, pemilu anggota DPRD selanjutnya yang dijadwalkan pada 2029 akan mundur hingga ke 2031.
Akibatnya, kata dia, anggota DPRD periode 2024-2029 berpotensi menjabat hingga tujuh tahun. Padahal, Pasal 22E UUD 1945 mengatur pemilu DPRD digelar setiap lima tahun sekali. Mahfud berpendapat, perpanjangan masa jabatan anggota DPRD seharusnya hanya bisa dilakukan dengan jalan mengubah UUD. “Yang boleh memperpanjang jabatan (anggota DPRD) itu hanya konstitusi itu sendiri,” tuturnya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) 2019-2024 itu juga menilai putusan MK tersebut tidak konsisten, karena sebelumnya MK sudah pernah memutus perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Dalam putusan-putusan MK terdahulu, kata Mahfud, bentuk penyelenggaraan pemilu yang ada saat ini dinyatakan sudah konstitusional. Namun putusan MK yang terbaru justru menyatakan bentuk pemilu harus diubah karena tidak sesuai dengan konstitusi. “Itu yang disebut inkonsisten,” katanya.
Penjelasan Mahfud ini berbeda dengan pendapat sejumlah pakar hukum tata negara lainnya. Pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah, misalnya, mengatakan munculnya norma-norma hukum baru dari MK bisa dibenarkan.
Dia mengatakan langkah MK bertindak sebagai legislator positif dan mengeluarkan norma sendiri bukanlah fenomena baru. “Urusan positive legislature itu sudah kerap kali dilakukan oleh MK,” kata Herdiansyah pada Rabu, 2 Juli 2025.
Herdiansyah menilai putusan MK yang melahirkan norma baru itu termasuk kategori judicial activism atau aktivisme yudisial. Artinya, kata dia, Mahkamah boleh menilai sendiri dan membuat norma baru jika pembuat undang-undang tidak membuat norma yang sesuai dengan kepentingan publik.
Sebelumnya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan MK tidak melanggar Pasal 22E UUD 1945 tentang pemilu. Dia mengatakan MK telah memberi mandat constitutional engineering atau rekayasa konstitusi kepada DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang untuk menindaklanjuti putusan soal pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal.
“Tidak ada pelanggaran karena MK juga menegaskan agar pembentuk UU melakukan constitutional engineering terkait dengan peralihannya. Sebagaimana misalnya ketentuan peralihan yang pernah diatur dalam UU pilkada yang lalu untuk kepentingan pilkada serentak,” kata Enny, yang juga merupakan juru bicara MK saat dihubungi pada Senin, 7 Juli 2025.
Menurut dia, rekayasa konstitusi dimaksud hanya untuk satu kali pemilihan sebagai konsekuensi masa transisi. Enny menjelaskan putusan Mk soal pemisahan pemilu nasional dan daerah sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari putusan MK sebelumnya. Dia menyinggung Putusan Nomor 55 Tahun 2019 yang telah menegaskan keserentakan pemilu. Dalam Putusan 55, MK menegaskan model keserentakan yang dapat ditentukan oleh pembentuk UU, termasuk salah satu modelnya adalah pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Enny, dengan melihat praktik penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berlangsung 2019, 2024, dan sebagai upaya mewujudkan pemilihan yang lebih demokratis ke depan dengan tetap menjaga keserentakan pemilu, “maka pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menjadi hal yang konstitusional.”
Sultan Abdurrahman, Dian Rahma Fika, Daniel Ahmad Fajri, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Menyoal Hak Digital dalam Transfer Data Pribadi WNI ke AS
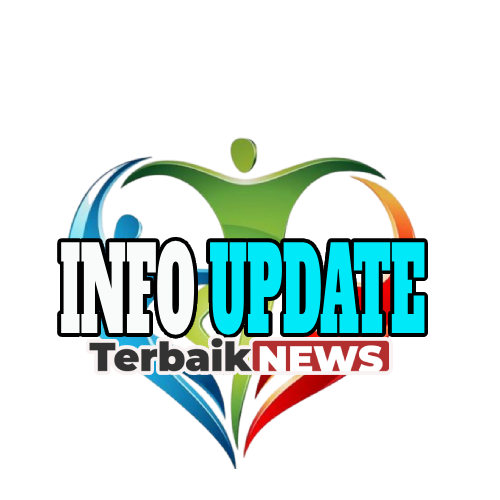


















:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4694484/original/014014900_1703158472-Snapinsta.app_369394705_681011023450360_8184077345776272812_n_1080.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5250743/original/013684300_1749731297-20250612_145520.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5210274/original/024665900_1746503629-000_44K29DW.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4980574/original/003676000_1729917598-063_2181088347.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5164369/original/027401300_1742169870-20250317-Atl_Madrid_vs_Barcelona-AFP_4.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5232068/original/000055400_1748194700-erling_haaland_selebrasi_fulham_man_city_250525_ap_dave_shopland.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3364126/original/096432300_1612065262-Palmeiras_Vs_Santos_21_06.JPG)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5207394/original/061933800_1746227857-AP25122711287596.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5255030/original/026746900_1750147361-Depositphotos_522512270_XL.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5249182/original/004975000_1749630148-m55ubj6i.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4477886/original/038758100_1687477004-5170003.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4988811/original/048786100_1730584559-Newcastle_United_vs_Arsenal_2024-4.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5096102/original/040080600_1736981191-AP25015759566846.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5250789/original/086563400_1749732792-trent_alexander-arnold_real_madrid_preskon_valdebebas_ap_manu_fernandez_01.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4850266/original/060481000_1717295438-000_34UP24M.jpg)
