TEMPO.CO, Yogyakarta - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid melontarkan kritik terhadap intelektual kampus yang diam melihat berbagai pelanggaran kebebasan akademik dan berekspresi sebagai pilar penting demokrasi.
Keresahan itu Fathul sampaikan dalam diskusi publik yang digelar Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII bertajuk Membongkar Brutalitas Aparat Kepada Mereka yang Tak Sejalan dengan Rezim di Selasar Auditorium Prof Kahar Muzzakir UII pada Senin sore, 30 Juni 2025.
Diskusi ini merespons berbagai bentuk kekerasan, teror, dan intimidasi polisi maupun tentara dalam sejumlah protes mahasiswa menentang berbagai kebijakan pemerintah, misalnya pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Belum lama ini, tiga mahasiswa Fakultas Hukum UII mendapatkan teror dan intimidasi karena mengajukan gugatan UU TNI ke Mahkamah Konstitusi. Fathul pasang badan membela tiga mahasiswanya dengan menyediakan bantuan pendampingan hukum.
Doktor Departement of Information System University of Agder, Kristiansand, Norwegia itu menyebutkan intelektual kampus yang terdiri dari mahasiswa dan dosen kini terlalu terlena dengan berbagai kenyamanan sehingga tak punya sensitivitas terhadap pelanggaran kebebasan akademik dan berekspresi. Mahasiswa dan dosen sebagai kalangan elit, menurut dia juga tidak peka terhadap berbagai ketidakdilan, penyimpangan, dan ketimpangan. Padahal mereka merupakan kalangan yang punya keistimewaan karena mengenyam pendidikan tinggi yang seharusnya lebih tercerahkan. “Bisa jadi mereka diam karena dikondisikan melalui beragam cara,” kata Fathul.
Publik mengenal lelaki 51 tahun itu secara tegas menolak Revisi UU TNI, tidak seperti pimpinan sejumlah kampus lainnya yang cenderung diam. Dia ikut dalam demonstrasi penolakan Revisi UU TNI yang mengembalikan Dwifungsi ABRI di Balairung UGM pada 18 Maret 2025 bersama sejumlah dosen dan aktivis. Selain itu, Fathul kerap terlibat dalam forum-forum diskusi bersama sejumlah aktivis, jurnalis, dan berjejaring dengan banyak kalangan yang kritis terhadap pemerintah, termasuk seniman.
Dia menilai intelektual kampus saat ini tak banyak bersuara karena dikondisikan untuk mengurus hal-hal yang sifatnya administratif dan berbagai program yang menyita energi. Selain itu, minimnya kesadaran kolektif menjadikan mereka tak bisa bersuara kritis. Sebagian petinggi kampus, kata dia, khawatir suara kritis itu berdampak pada karir, keberlangsungan lembaga, dan tersendatnya anggaran dalam bentuk hibah.
Persoalan lainnya, kata Fathul, mereka tak berusaha mencari informasi alternatif yang menunjukkan fakta-fakta terjadi pelanggaran kebebasan akademik dan berekspresi. Rektor dan dosen kerap diam karena merasa itu bukan hak yang layak diperjuangkan. Intelektual menurut dia punya peran penting membangun narasi kritis demi menjaga tegaknya demokrasi. "Masalahnya kampus sudah nyaman, yang penting dapat hibah,” ujarnya.
Pemberangusan kebebasan akademik dan berekspresi, kata Fathul bertentangan dengan semangat reformasi yang menekankan pada pentingnya kebebasan sipil. Menurut dia, penerapan demokrasi di Indonesia saat ini palsu. Warga negara seolah-olah boleh bicara, tetapi pemerintah seringkali tak mau mendengarkan suara, gagasan, dan partisipasi mereka secara serius. “Aspirasi rakyat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat,” kata dia.
Fathul mendorong intelektual berani bersuara kritis berbasis pada data, fakta, dan verifikasi. Dengan pendekatan ilmiah itu, intelektual memiliki pengetahuan yang cukup sehingga lebih mudah bersikap tegas dalam menyuarakan sesuatu.
Pilihan Editor: TNI Masuk Kampus, Koalisi Sipil Anggap Pola Orde Baru Hidup Lagi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
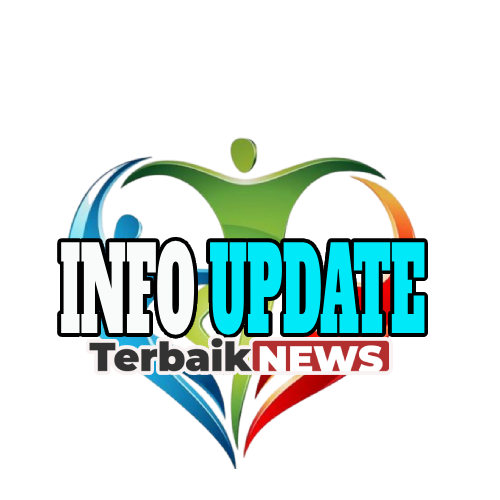




















:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4477886/original/038758100_1687477004-5170003.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5255030/original/026746900_1750147361-Depositphotos_522512270_XL.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4612735/original/020424700_1697457852-vitaliy-zalishchyker-tQCFYZ1bLJE-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5257817/original/036802900_1750323375-Foto_2__1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5263985/original/055426600_1750836434-20250624_132213.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2398030/original/091901500_1541069016-000_RT6DY.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4736827/original/080231300_1707275018-centre-for-ageing-better-REIecbS8XQY-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5253041/original/077589100_1749985206-Gustiwiw_0.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5260647/original/020898900_1750600945-snapsave-app_3660387958873942474.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5252878/original/068050400_1749972944-WhatsApp_Image_2025-06-15_at_14.22.31.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1785875/original/014960600_1512003954-20171129-Daftar-Pemenang-SCTV-Awards-2017-Herman-7.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1412499/original/060192700_1479737232-20161121--Prilly-Latuconsina-Jakarta--Herman-Zakharia-02.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5224553/original/050243100_1747634982-obesitas.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4946420/original/058289700_1726622725-20240918-Real_Madrid_vs_Stuttgart-AFP_6.jpg)

